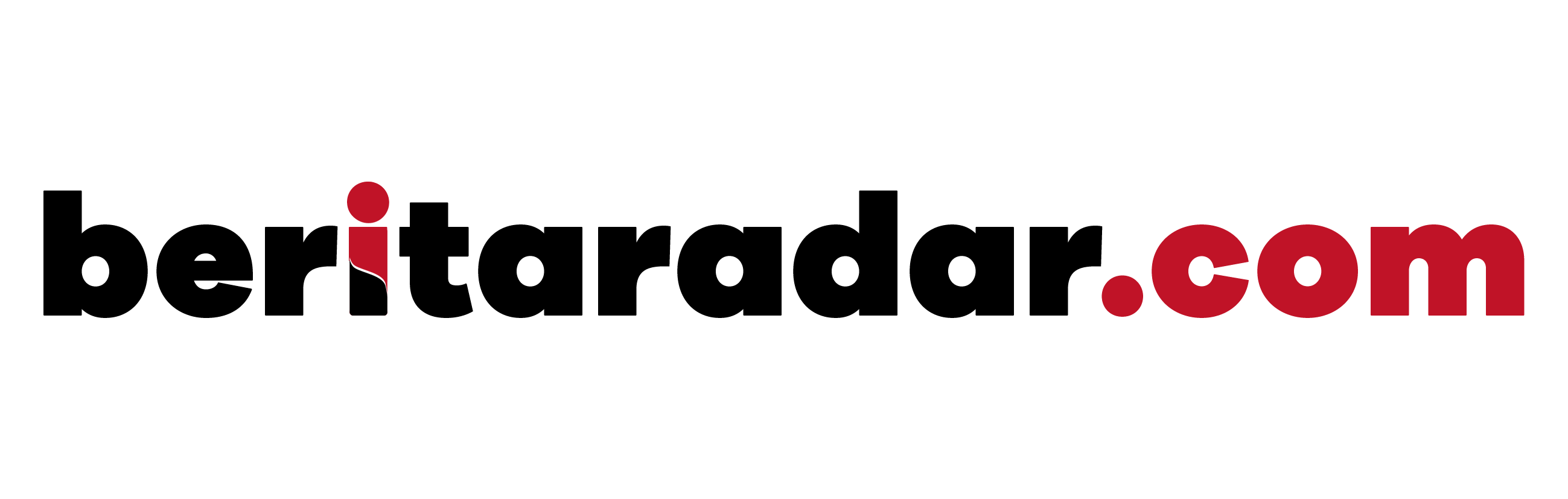TANAH selalu jadi api dalam sekam. Sengketa tanah pun tak henti mewarnai sejarah Indonesia. Kali ini, para petani Jambi dan Suku Anak Dalam sudah sebulan berkemah di lahan kosong depan kantor Kementerian Kehutanan. Bahkan sejumlah petani melakukan long march sejauh 1.000 kilometer dari Jambi menuju Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut lahan dan hutan mereka, yang terkikis akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Konflik agraria tersebut membuktikan apa yang dikatakan Mochammad Tauhid, tokoh penting dalam pemikiran agraria di Indonesia: “Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.”
Konflik agraria sudah terjadi sejak zaman kolonial. “Kasus sengketa tanah terjadi karena adanya pemberian hak oleh pemerintah,” kata Mohammad Iskandar, pengajar di program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia.
Pada 1870 pemerintah kolonial memberlakukan Undang-undang (UU) Agraria (Agrarisch Wet) yang memberikan hak erfpacht –sekarang Hak Guna Usaha– kepada para pemodal asing untuk mengusahakan perkebunan.
“Tanah menjadi sumber konflik karena tanah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan penduduk pribumi dijadikan buruh,” ujar Idham Arsyad, sekretaris jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria.
Hak erfpacht menggusur tanah pertanian rakyat karena asas domein verklaring, bahwa tanah yang tak bisa dibuktikan milik seseorang dianggap milik negara, dan negara melemparkan hak pengelolaan kepada para pengusaha. “Orang pribumi tidak bisa bersaing dengan orang kaya Eropa yang mampu membeli banyak tanah,” kata Iskandar.
Para petani kemudian melakukan perlawanan; seringkali dibalut fanatisme keagamaan. Antara lain peristiwa Cikandi Udik (1845), kasus Bekasi (1868), kasus Amat Ngisa (1871), pemberontakan Cilegon (1888), kerusuhan Ciomas (1886), pemberontakan Gedangan (1904), pemberontakan Dermajaya (1907), peristiwa Langen di Banjar, Ciamis (1905), peristiwa Cisarua dan Koja, Plered (1913-1914), dan peristiwa Rawa Lakbok, Ciamis (1930).
Ketika Belanda ditaklukkan Jepang, banyak perkebunan besar milik perusahaan Belanda dan asing ditinggalkan dan terlantar. Militer Jepang mendorong rakyat untuk mengolah dan menanaminya dengan bahan kebutuhan perang seperti jarak dan sereh wangi.
“Dengan izin dan dorongan pemerintah Jepang itulah maka tercipta persepsi di kalangan rakyat bahwa mereka memperoleh kembali tanah mereka yang dulu melalui rekayasa hukum dirampas oleh Belanda,” tulis Gunawan Wiradi dalam Seluk Beluk Malasah Agraria. Toh, pemberontakan petani tetap terjadi seperti di Indramayu pada 1944, karena rakyat tak sanggup menanggung penindasan.
Setelah kemerdekaan, penggarapan tanah perkebunan oleh rakyat berlanjut. “Pemerintah Indonesia meneruskan sikap toleran Jepang dengan membiarkan rakyat menduduki tanah, sambil menunggu payung hukum agraria nasional terbentuk,” tulis Ahmad Nashih Luthfi dalam Melacak Sejarah Pemikiran Agraria.
Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 13 tahun 1946 untuk menghapus desa-desa perdikan, yang bebas pajak, di mana elite-elitenya menguasai sebagian besar tanah di desa-desa. Pemerintah juga mengeluarkan UU No 13 tahun 1948 untuk mengambil-alih semua tanah 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta.
Celakanya, hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) menjungkirbalikkan kebijakan reformasi agraria tersebut. Salah satu syarat pengakuan kedaulatan Indonesia antara lain aset milik Belanda harus dikembalikan dan dijamin. Deli Planters Vereniging, asosiasi pengusaha tembakau, ingin menguasainya kembali sesuai kesepakatan KMB. Pada 1953, petani miskin di Deli, Sumatra Utara, melakukan perlawanan: 21 orang tertembak, enam di antaranya tewas dalam peristiwa yang kelak dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Morawa.
Peristiwa itu mendapat sorotan dari media maupun parlemen. Partai Komunis Indonesia (PKI) mencemooh menteri dalam negeri Mohamad Roem dengan sebutan “Mohamad Roem Traktor Maut”. Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya, yang mendapat dukungan dari Partai Nasional Indonesia. Perdana Menteri Wilopo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.
Penyair Agam Wispi yang menyaksikan para petani digusur dengan traktor dan bedil, mengabadikannya dalam puisi “Matinya Seorang Petani”: Depan kantor bupati/tersungkur seorang petani/karena tanah/karena tanah. (*)