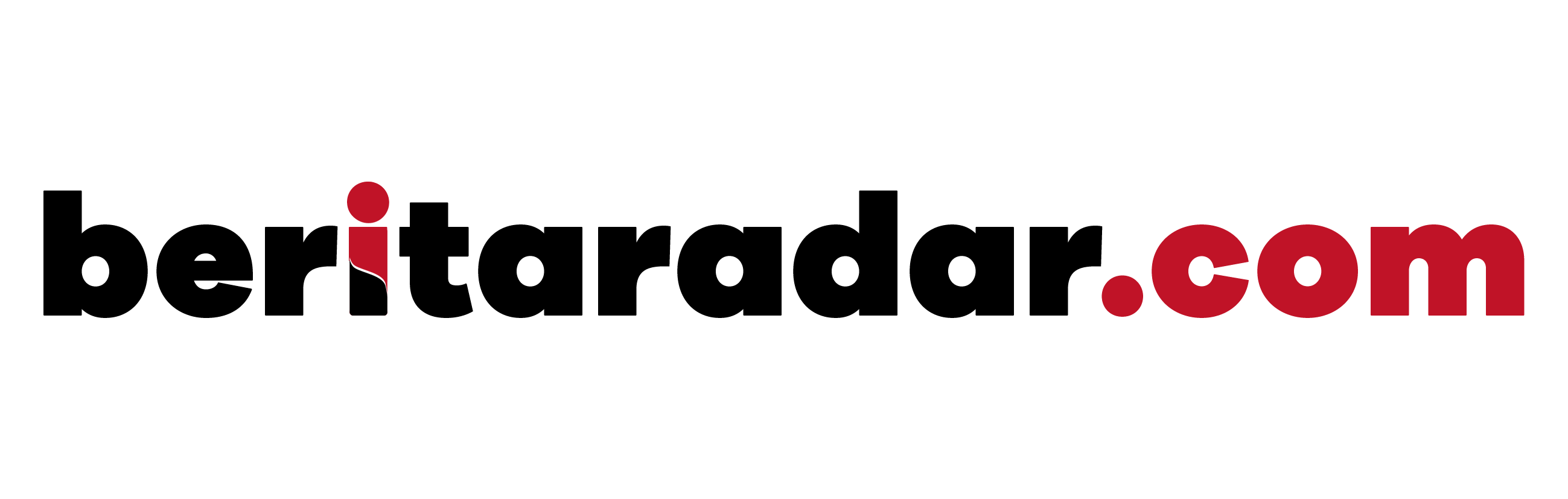HARI ini, 30 September, lima puluh empat tahun lalu dimulai tragedi berdarah yang masih menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.
Ribuan bahkan jutaan orang — utamanya anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) — dilaporkan tewas terbunuh dalam pembantaian massal 1965.
Insiden tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S).
Saat itu, Rusdian Lubis masih berusia 12 tahun. Ia mengingat kembali kejadian yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya.
Di bawah ini adalah petikan dari memoarnya yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia, berjudul Anak Kolong di Kaki Gunung Slamet tentang peristiwa seputar G30S.
Rusdian kini adalah seorang environmentalist. Ia pernah bekerja di pemerintahan, lembaga internasional (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia), dan seorang Eisenhower Fellow.
Memoar ini diambil dari kacamata seorang anak kolong berumur 12 tahun, bukan analisa sejarah, melainkan cerita keluarga. Dirangkum kembali dengan izin penulis.
Akhir September 1965, situasi politik di Wonopringgo mulai panas tetapi masih terkendali. Tidak ada bentrokan fisik serius seperti di Jawa Timur. Antar kelompok hanya saling mengejek, di mana ada kesempatan.
Kokam (Komando Keamanan) Muhammadiyah sering jadi bahan tertawaan PKI, PNI, dan NU karena singkatan “Kokam” sering diplesetkan menjadi “kon*** kambing”. Ini membuat muka guru-guru kami yang juga anggota Kokam — Pak Ani dan Pak Asyik — merah padam!
Suatu hari Pak Asyik masuk ke kelas dengan pakaian loreng Kokam. Dengan muka serius dia memberi tahu para siswa agar hati-hati jika didekati orang-orang tak dikenal. Desas desus tentang penculikan yang dilakukan oleh PKI makin sering terdengar. Wonopringgo juga tak terlepas dari desas desus itu.
Kabarnya penculikan terjadi di pedesaan di daerah pegunungan kapur di selatan kota yang mempunyai kantong-kantong PKI. Kabar lain, PKI telah menyiapkan kuburan massal di hutan-hutan jati dan membuat alat pencungkil mata.
Anak-anak di atas 10 tahun akan dibunuh, sedangkan mereka yang di bawah umur itu akan dirampas sebagai anak negara dan dimasukkan ke kamp re-edukasi seperti di negara komunis. Kami tidak tahu kebenaran kabar ini, tetapi rasa takut makin hari makin menjadi-jadi. Suasana mencekam pelan-pelan membuat keluarga tentara ketakutan.
Aku tidak terpengaruh. Kegiatanku berjalan seperti biasa. Pagi sampai siang aku sekolah, sore ikut mengaji di langgar (surau) sambil memasang pancing di sungai dekat jembatan. Tetapi sejak pasukan Yonif 407 berangkat tugas ke Sumatera, suasana sekitar asrama memang menjadi tintrim (sepi mencekam).
Ini diperburuk dengan oglangan (giliran mati lampu) yang amat menjengkelkan. Hampir tiap malam aku belajar dengan diterangi lampu senthir atau lampu teplok berbahan bakar minyak tanah. Pagi hari, asap hitam atau langes terkadang masih membekas di hidungku.
PKI mempunyai ranting atau anak cabang organisasi serta onderbouw-nya seperti Gerwani. Ibu kenal cukup baik dengan seorang aktivis Gerwani yang rajin menyambangi ibu-ibu asrama Yonif 407. Wanita itu manis dan amat grapyak (pandai bergaul dan ramah).
Kantor partai itu adalah bangunan bercat putih bertingkat dua, terletak di pinggir jalan dan berhadapan dengan warung es. Di halaman kantor ada sebuah papan pengumuman yang ditempeli Koran Harian Rakyat (HR) untuk dibaca mereka yang lewat.
Aku sering mampir untuk membaca berita dan kartun-kartun HR yang bersemangat. Menjelang 30 September, kubaca berita tentang tuntutan PKI untuk membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). DN Aidit dalam rapat raksasa CGMI (organisasi mahasiswa PKI) pernah berpidato: “Kalau tidak berhasil membubarkan HMI, maka anggota-anggota CGMI mengganti celana dengan sarung”.
Pernyataan ini tidak membuat marah kaum sarungan (golongan Islam, terutama NU dan Muhammadiyah) tetapi malah menggembirakan pedagang sarung batik di Pekalongan. Karena pangsa pasar sarung akan terbuka lebar menjangkau warga PKI. Tapi tidak berpengaruh di Nopringgo, sebab warga PKI juga pakai sarung kemana-mana. Di kota kecil ini semua anggota partai atau golongan adalah kaum sarungan!
Tepat pada 30 September 1965, koran HR memuat pernyataan tokoh PKI Anwar Sanusi, “Ibu Pertiwi hamil tua, dan paraji (dukun beranak) sudah siap untuk kelahiran sang bayi”.
Tanggal 30 September 1965, Ibu Pertiwi akhirnya melahirkan, tetapi bukan bayi montok yang lucu. Peristiwa G30S/PKI meletus di Jakarta! Sehari kemudian aku dengar berita RRI Jakarta: Pengumuman tentang Dewan Jenderal, berita tentang pemberontakan PKI, penculikan tujuh jenderal dan dibunuh di Lubang Buaya, disusul pengumuman-pengumuman lain yang amat membingungkan.
Kami juga dengar berita dari RRI Yogyakarta: PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Semua berita menyeramkan itu aku dengar dari radio transistor Ayah merk Phillips warna biru.
Sejak itu suasana Wonopringgo menjadi amat menakutkan. Tahun-tahun yang gelap dimulai. Aku selalu ikuti kabar nasional melalui RRI dan dari koran Berita Yudha yang tiap hari diantar petugas piket ke rumah. Kabar lokal kudapat melalui “kelompok diskusi” di warung es dekat rumah Pak Guru Casbani.
Di warung itu berkumpul tokoh–tokoh informal Wonopringgo, kebanyakan dari NU dan PNI. Golongan hitam seperti Yitno, si Gemuk dan si Kurus kadang-kadang ikut bergabung; Serma Hadi juga sekali-sekali mampir ke warung es itu. Sebagai anak kecil aku tidak ikut diskusi, cuma nguping kabar tentang bentrokan antara massa PKI dan massa Islam di desa-desa sekitar Wonopringgo. Kemudian berita pembunuhan oleh PKI kepada anggota PNI dan NU dan pembalasan dendam oleh NU dan PNI kepada anggota PKI.
Kabarnya, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi paramiliter seperti barisan Ansor NU dan Banra PNI melakukan pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mayat-mayat dibuang di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas.
Saat itu terjadi “histeria massa” yang tak terkendali, pilihannya hanya membunuh atau dibunuh. Rasa takut atau dendam bisa membuat manusia menjadi amat kejam. Mereka berbunuhan dengan segala alasan: Perselisihan pribadi, karena hutang tak terbayar, masalah sengketa tanah, cinta ditolak atau karena punya “indikasi terlibat” G30S/PKI. “Indikasi” menjadi kata yang menakutkan.
Di Wonopringgo, suatu hari ada kejadian mayat terapung di bendungan Kali Kletak. Lain hari di Kali Krempyeng tempat anak-anak kolong Yonif 407 biasa memancing. Aku tidak melihat mayat itu dengan mata kepalaku, hanya melihat segerombolan orang berkerumun di pinggir kali. Ibu melarangku melihat mayat dan pembunuhan.
Di Pekalongan, kabarnya, puluhan mayat terapung di laut sehingga banyak ikan laut tidak laku dijual karena ada cerita orang menemukan jari tangan di perut ikan besar. Semua ini kabar yang kudengar dari jalanan dan di sekolah. Di samping “warta berita” dari warung es itu, guru-guru kami juga menjadi sumber berita. Anak-anak sudah tidak peduli dengan pelajaran sekolah lagi, tetapi asyik mendengarkan cerita Pak Asyik.
Kabar-kabar itu kuceritakan ke Ibu yang berusaha tampak tenang tapi sebenarnya amat ketakutan. Ibu makin ketat mengatur anak-anak terutama di sore hari. Mulai saat itu aku hanya boleh mengaji sampai Isya di surau. Jika kami dulu boleh main ke asrama (rumah komandan di luar asrama) sampai setelah Isya, sekarang hanya dibatasi sampai habis Mahghrib.
Di sore hari, kami lebih banyak berkerumun dekat radio. Suatu kali, Ibu bercerita tentang keganasan peristiwa Madiun tahun 1948. Seorang paman Ibu, administrator pabrik gula di Gorang-Gareng, Madiun, dibunuh secara keji dan dimasukkan ke dalam sumur oleh PKI. Ibu dan Bulik Diati yang kebetulan berlibur di perkebunan itu hampir menjadi korban jika pasukan Siliwangi tidak keburu datang menyelamatkan.
Komandan tentara penjaga menganjurkan agar kami pindah ke dalam kompleks asrama, tetapi Ibu menolak. Rumah komandan memang di luar kompleks. Kami cukup aman. Di samping tentara jaga, beberapa peronda dari kampung juga menyambangi rumah-rumah warga termasuk rumah kami yang hampir menyatu dengan kampung. Serma Hadi dari Babinsa, sahabat Ayah, juga selalu berkeliling tiap malam.
Suatu malam sekitar jam 11, terdengar bunyi ketukan yang cukup keras di pintu belakang dekat dapur atau “pintu butulan” yang menghadap ke pagar kawat berduri. Di seberang pagar itu terhampar sawah luas diapit dua sungai kecil yang dibatasi sebuah lembah. Kali Duwur di sebelah atas dan Kali Ngisor di sebelah bawah.
Ibu segera membangunkan aku dan menyuruhku diam supaya adik-adikku tidak panik. Ketukan makin keras tetapi tidak ada tanda menggedor atau mendobrak. Ibu mulai ketakutan, tetapi aneh aku cukup tenang.
Kubuka laci meja dekat jendela untuk mengambil pisau belati Ayah, lalu aku mengendap-endap menghampiri pintu. Tindakan ini sebenarnya salah dan berbahaya. Seharusnya kami mengintip jendela depan dan memanggil penjaga di sana. Tetapi keinginan tahuku mengaburkan nalar.
Pisau belati Ayah bergagang tanduk sepanjang 25 cm itu tidak cukup tajam. Lengan Tam pernah kuiris dengan pisau itu dan tidak banyak mengeluarkan darah. Selain ini, ada dua pisau belati di rumah, belati lempar tipis runcing dan belati komando model Bowie besar dan tajam. Keduanya dibawa Ayah ke medan tugas.
Aku dekati pintu pelan-pelan, Ibu makin gemetaran dan tangannya bergerak-gerak seolah menghapalkan jurus beladiri tangan kosong yang dipelajarinya di Purwokerto. Mulutnya komat kamit atau ndremimilberdoa campur aduk dan menggumam tidak jelas. Ibu membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas yang disebutnya Al-Patekah dan Kulhu. Saat itu, Ibu memang baru belajar menghapal beberapa surat Al-Qur’an dibimbing Yu Rah, si tukang cuci merangkap guru mengaji tidak resmi.
Setelah dua tiga kali membaca, Ibu merasa kedua surat itu tidak cocok untuk menghadapi situasi ini. Lalu dia membuat tanda salib dan menggumamkan sebuah doa Katolik. Ibu memang dibesarkan dalam tradisi Katolik oleh Eyang Mujo, adik Kakek. Tetapi Ibu juga ragu-ragu apakah doa itu akan memecahkan persoalan.
Ibu diam sebentar menarik nafas, tiba-tiba dari bibirnya pelan-pelan mengalir tembang Dandhanggula Mantraweda karangan Sunan Kalijaga:
//Ana kidung rumekso ing wengi/ teguh hayu luputa ing lara/ luputa bilahi kabeh/ jim setan datan purun/ paneluhan tan ana wani/ miwah panggawe ala/ gunaning wong luput/ geni atemahan tirta/ maling adoh tan ana ngarah ing mami/ guna duduk pan sirna//
//Ada kidung yang menjaga malam / menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit / terbebas dari segala mala petaka / jin dan setan pun tidak mau (mendekat) / segala jenis sihir tidak berani / apalagi perbuatan jahat / guna-guna tersingkir / api menjadi air / pencuri pun menjauh dari aku / segala bahaya — ilmu hitam akan sirna //
Itulah kidung penolak bala yang sering dinyanyikan Eyang, khususnya setiap malam Jumat Kliwon di pendopo Solo. Atau sambil menggendong anak-anaknya dan kemudian cucu-cucunya yang rewel. Rupanya saat terdesak, maka dari dalam batin manusia mencuatlah ritual paling awal dan paling akrab, menutupi yang datang kemudian. Dengan keheranan, aku pandangi Ibu yang berdoa campur aduk itu, “Lho, Bu ?”
Ibu menukas, “Mbok wis ben tha! Dongane iki ben lengkap” (Sudah, biar aja! Doa ini biar lengkap).
Aku tak membantah dan menghindari debat teologis yang tak perlu.
Sampai itu, ketukan itu makin keras dan makin sering. Terpengaruh Ibu, aku juga menggumamkan sepenggal mantera Rajah Kalacakra yang pernah kubaca dari Primbon Betal Jemur milik Eyang: “Aum, Yamaraja-Jaramaya; Yamarani-Niramaya; Yasilapa-Palasiya” (Aum, siapa yang akan membuat bahaya, hilang kekuatannya; siapa yang akan membuat celaka, hilang niat buruknya; siapa yang akan membuat kelaparan, malah memberi makanan).
Rajah Kalacakra atau Sastra Bedhati itu dibaca dalang saat upacara ruwatan. Doa itu panjang, aku tidak ingat semua. Pintu lalu kubuka sedikit, ini juga kesalahan besar. Di antara sinar lampu 15 watt, aku melihat sesosok orang berbadan kekar berotot berkulit legam, tanpa baju, dan bercelana kolor hitam.
Di antara bunyi doa campur baur, Ibu bertanya dari belakangku: “Sapa kuwi?” (Siapa itu?).
Ketukan berhenti dan terdengar suara berat: “Kulaaa Bu Kompi” (Saya, Bu Kompi).
Ibu berhenti merapal doa. Tubuhnya lemas lalu duduk di bangku kayu di dapur, tapi wajahnya tampak lega. Puas, karena doa lengkapnya manjur. Aku membuka pintu dan melihat sosok hitam legam tanpa baju itu: The Great Rasbi!
Tangan kanannya menggenggam parang tajam dan tangan kirinya menenteng seikat ikan: gabus, sepat, bethik dll. Sambil tertawa lebar dia berkata, “Kula nembe ngoncor, Bu Kompi, niki iwake kangge Ibu”(Saya baru ngoncor, Bu Kompi. Ini ikannya untuk Ibu).
Pak Rasbi yang miskin tetapi baik hati segera berlalu. Setelah mengucapkan terima kasih, ikan–ikan itu kuambil dan kulemparkan ke ember cucian. Besok pagi Tam akan kusuruh “mbetheti”, membersihkan atau memeruti ikan. Aku tidur lagi. Sampai pagi, Ibu masih termangu-mangu. Sesuatu yang lebih buruk dari kejadian malam itu bisa terjadi setiap saat.
Suatu hari, bintara piket berkata bahwa situasi di Jawa Tengah, terutama di Solo dan daerah Istimewa Yogyakarta, makin gawat. Di pihak lain, pasukan-pasukan terkuat di Jateng tidak ada di tempat. Brigif IV dikirim ke Sumatera Utara dan Brigif V melaksanakan tugas Operasi Dwikora di Kalimatan Barat.
Kabar burung, Jawa Tengah memang sengaja dikosongkan atas perintah komandan tentara yang pro-PKI. Bintara piket itu bilang bahwa kemungkinan besar Yonif 407 akan segera ditarik pulang untuk mengisi kekosongan.
Berita itu benar. Brigif 4 yang berada di Sumatera Utara, pada tanggal 23 Oktober 1965, segera diperintahkan kembali ke Jawa Tengah guna mengatasi situasi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yonif 405 dan 407 kembali dari Sumatera dengan memakai kapal, mampir di Tanjung Priok, kemudian ke Semarang, lalu bersama-sama Yonif 406 menumpas G30S/PKI di daerah Surakarta (Ma Ko Brigade berkedudukan di Solo). Yonif 406 sudah ditempatkan di Klaten satu minggu terlebih dahulu.
Suatu malam, Ayah pulang ke rumah dikawal sekitar satu regu tentara bersenjata lengkap yang kemudian stelling (bersiaga) di halaman. Lampu halaman dimatikan, semua orang tampak tenang tetapi siaga. Serma Hadi juga ada di situ, kali ini dia tidak merokok.
Tidak sampai setengah jam, Ayah berbicara dengan Ibu, lalu menanyakan kabar tentang sekolahku dan adik-adikku. Ayah sangat terkejut waktu Ibu bilang didatangi seorang anggota Gerwani yang mengedarkan kertas. Suara Ayah keras, “Kamu tandatangani, enggak?”
Ibu menjawab tak kalah keras, “Ya ora…, goblok apa aku?”
Ayah kelihatan lega dan bergumam, “Ya wis, kalau kamu tandatangan, bisa-bisa kamu diciduk atau diselesaikan”.
Banyak kosa kata baru saat itu: digropyok, diciduk, diamankan, dilenyapkan, diambil, diselesaikan, dan dihabisi.
Setelah saling memberi hormat dengan Serma Hadi, Ayah melompat ke atas truk kecil hijau tua yang dikemudikan Serka Hartojo. Sopir, pengawal, dan sahabat Ayah yang setia itu selalu bersama hampir pada tiap operasi militer, bahkan sampai Operasi Seroja (1977-1978) di Timor Timur. Jeep itu menghilang di kegelapan malam melewati pebukitan Kajen kembali ke induk pasukan-pasukan 407 di Boyolali dan Surakarta.
Ayah kemudian menjadi caretaker bupati di suatu kabupaten karena bupati lama tersangkut G30S/PKI. Malam itu, wajah Ayah tampak serius dan angker, “Jaga Ibu dan adik-adikmu”.
Tanpa menyadari kegawatan situasi ini, aku malah asyik melihat tentara beraksi, bergerak dengan sistematis dan disiplin. Aku anak kolong. (*)