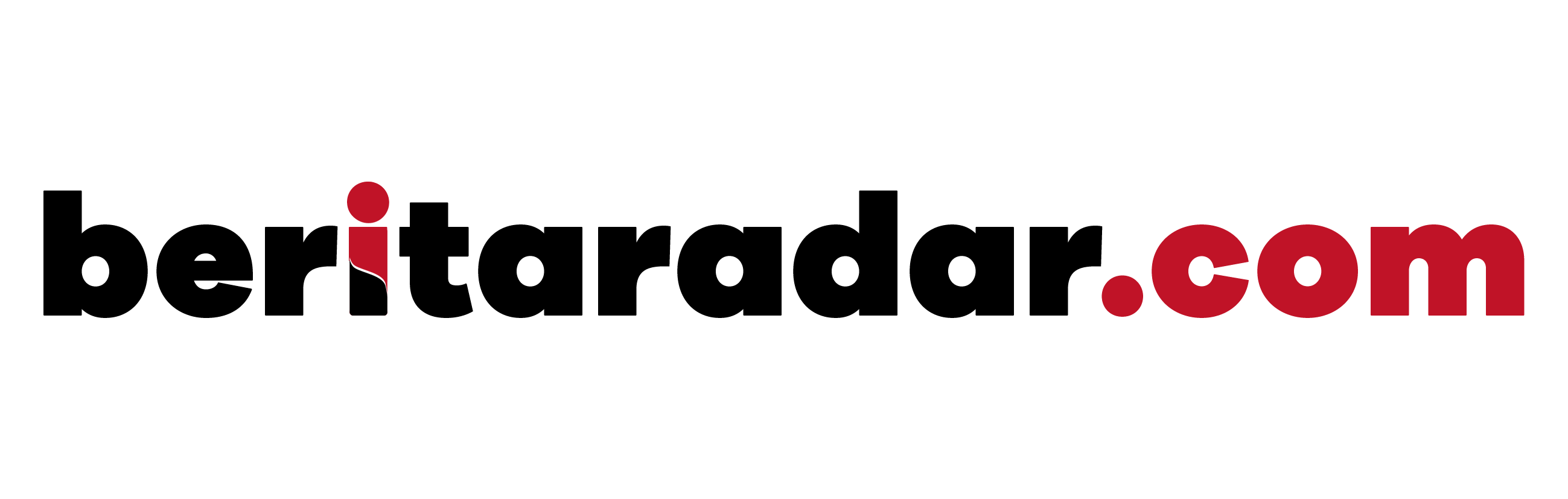POLISI menciduk dua preman yang kerap bikin resah para pedagang dan pelintas Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/9). Aksi para pemuda tersebut viral di dunia maya karena memalak para pengendara yang melintas.
“(Preman) diamankan Kamis sekira pukul 13.45 WIB. Di Pintu Keluar Blok F Pasar Tanah Abang,” ungkap Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan, dalam keterangannya, Jumat (6/9).
Kedua pelaku adalah Supriyatna (20), warga Kampung Bali, Tanah Abang dan M Nurhasan (39) warga Bekasi yang tinggal di Tanah Abang. Dari tangan Supriyatna, polisi mengamankan barang bukti uang hasil palak sebesar Rp54 ribu.
Akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki menjadi salah satu pihak yang melaporkan kejadian tersebut. Dalam video yang diunggah Koalisi Pejalan Kaki, para preman yang diketahui lebih dari dua orang itu memalang kendaraan, dan memaksa pengemudi membuka kaca dan menyerahkan uang.
Kemudian, peristiwa tragis dialami Mohammad Rozian (17) warga Jl Puyau 25, Komplek Ratu Elok Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Remaja yang merupakan santri Ponpes Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan ini meninggal dunia setelah ditusuk orang bertato tak dikenal .
Informasi yang diterima radarcirebon.com jaringan portal beritaradar.com menyebutkan, peristiwa ini terjadai, Jumat malam (6/9), sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan DR Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon atau tepatnya di seberang Toko Buku Gramedia.
Di Indonesia, kata preman identik berbadan penuh tatto, berambut panjang, tampang sangar dan sempoyongan, senjata tajam, suka mabuk, parkir liar, pengamen jalanan, pengatur antrian angkutan umum, penjaga keamanan liar, pemungut restribusi liar, suka membuat keonaran dan diduga sebagai sampah masyarakat.
Jika mengacu pada definisi premanisme menurut situs Wikipedia, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.
Istilah “preman” sendiri diturunkan dari bahasa Belanda vrijman,yang secara harfiah berarti “orang merdeka”. Dalam bahasa kekinian istilah itu lazim digunakan untuk merujuk kepada penjahat kecil, tukang palak, atau berandalan.
Hingga 1980an, kata “preman” merujuk secara khusus kepada perwira militer tanpa seragam. Seiring waktu kata itu semakin berkonotasi kriminalitas, yang merepresentasikan pemahaman ihwal perpaduan antara kekerasan publik dan privat, serta ambiguitas antara legalitas dan ilegalitas yang mencirikan rezim Orde Baru.
Sejak kapan istilah “preman” menjadi bagian dari kebudayaan kita?
Sebelum kedatangan Belanda, lanskap sosial di Nusantara dibumbui oleh pusparagam penyamun, pendekar, tentara bayaran, ahli suluk, panglima perang, para pangeran dan sejumlah orang kuat, serta kelompok-kelompok pengguna kekerasan yang tinggal dalam apa yang didedahkan oleh sejarawan Henk Schulte Nordholdt sebagai “hidup bersama yang saling bermusuhan”.
Realitas politik ini oleh para ahli sejarah dicirikan sebagai sebuah “negara pertikaian”. Yaitu negara di mana pemberlakuan kontrol efektif apa pun atas penduduk setempat dan sumber daya alamnya membutuhkan negosiasi terus-menerus, pembentukan dan pembubaran persekutuan, di samping ritual pameran kekerasan yang secara buas bersifat pragmatis.
Kondisi ini memudahkan pertumbuhan aneka bentuk campuran antara kekerasan publik dan privat yang pelaksanaannya disubkontrakkan ke pihak liyan. Dari sanalah orang-orang kuat setempat yang masyhur sebagai “jago” menjadi salah satu sosok yang paling menonjol.
Kendatipun sudah menjadi praktik umum bagi para jago untuk menyerang, menyerbu, dan menjarah desa-desa tetangga, mereka kerap sangatlah protektif terhadap komunitas mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan kesetiaan dari masyarakat, walaupun kesetiaan itu juga dilandasi sebagiannya oleh rasa takut akan konsekuensi yang mungkin didapat apabila dikhianati.
Simpulan tak terelakkan yang dicapai oleh rakyat adalah kekuasaan dan kejahatan itu sebangun.
Kedatangan dan perluasan berangsur kuasa kolonial Belanda tidak mengganggu posisi jago. Baru pada abad ke-19, seiring dengan menguatnya pemerintahan yang terorganisir secara birokratis, peran mereka bergeser. Alih-alih menjadi sasaran represi, jago menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan kolonial, hasil dari proses pembentukan negara yang tersendat. Pemerintah kolonial berpusat di Batavia, tetapi jangkauan efektifnya tidak banyak yang sampai ke jantung pedesaan Jawa.
Untuk mengonsolidasi kekuasaannya, Belanda mengukuhkan pemerintahan tak langsung yang bersifat paralel, dikepalai oleh para pejabat pribumi yang dikenal sebagai bupati dan pangreh praja untuk memerintah Jawa. Di tingkat desa, semua yang menyerupai monopoli atas kekerasan berada dalam wilayah jago. Oleh karena itu setiap upaya untuk mengukuhkan “tatanan” mau tidak mau harus mengikutsertakan mereka.
Evolusi preman
Meski keadaan di Batavia (Jakarta) berbeda, tetapi di sini pun jago juga tampil sebagai tokoh-tokoh yang membentuk apa yang oleh sejarawan Robert Cribb teroka sebagai “jejaring yang berdiri di luar hierarki kewenangan pemerintah, antagonistik kepadanya, tetapi tidak sepenuhnya memusuhinya”. Sebagai masyarakat yang nyaris sepenuhnya berpijak pada perniagaan, di rezim kolonial, para majikan beserta rombongan mandor dan jago-jago mereka berperan utama bagi kehidupan ekonomi kota itu.
Dalam konteks inilah istilah vrijman memasuki bahasa sehari-hari untuk melukiskan sebuah jenis baru jago perkotaan, pengusaha lepas di bidang kekerasan yang tidak mengabdi kepada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), tapi diizinkan berada di Hindia, dan menjalankan kerjanya demi kepentingan VOC. Dalam sebuah masyarakat yang terikat hukum, vrijman hadir di wilayah legal dan konseptual nan abu-abu, bekerja di dalam sekaligus di luar hukum.
Pada peralihan abad, makin birokratisnya pemerintahan kolonial membuat jago perlahan-lahan termarjinalkan. Mereka tergusur dari peran tradisional mereka dalam kehidupan pedesaan dan juga posisi politik mereka sebagai penengah dan makelar kekuasaan. Status mereka kian bergeser menjadi sekadar “penjahat” dan “pelanggar hukum”.
Selama pendudukan Jepang, geng-geng terorganisir digilas. Karena itulah, saat Jepang kemudian dilucuti dan ditarik mundur secara bertahap pada 1945 sesudah tiga tahun berkuasa dengan kejam, ada jurang kekosongan yang ditinggalkannya.
Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tetapi pemerintahan yang mereka pimpin sesungguhnya tidak benar-benar ada. Di seantero tanah air, struktur kekuasaan formal negara yang dikukuhkan oleh pasukan pendudukan Jepang tumbang berguguran dan membuahkan pertempuran lokal yang kerap ganas demi memperebutkan kekuasaan dan sumber daya.
Kembalinya pasukan Belanda dan Sekutu pada 1945 mengawali kurun empat tahun perang gerilya berkesinambungan, dilancarkan oleh kelompok-kelompok mandiri lokal yang tak terpermanai jumlahnya, yang umumnya bergerak di luar kendali negara yang masih bayi itu.
Yang mempersatukan mereka hanyalah penolakan terhadap kembalinya kekuasaan Belanda. Milisi, gerombolan jago, dan geng-geng perkotaan membentuk bagian utama perlawanan terorganisir yang sering melangkahi tentara republik resmi.
Pasca pengakuan kemerdekaan 1949, salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah republik dan proyek konsolidasi lembaga-lembaga negara adalah bagaimana baiknya menyatukan laskar dan milisi jago. Sebagian mendapatkan tempat di dalam tentara nasional yang anyar, tetapi sebagian besarnya kembali ke kampung mereka masing-masing. Dengan sedikit keahlian dan sedikit kesempatan kerja, banyak yang merantau dan mencari nafkah dengan menggarong dan melakukan kejahatan-kejahatan kecil di Jakarta.
Selama Orde Baru, geng-geng preman kian terlembagakan. Antropolog Ian Douglas Wilson dalam buku barunya, Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia pasca Orde Baru (Marjin Kiri, Desember 2018) dengan cerkas meanggit, bahwa banyak di antaranya berada di garis depan pembantaian terencana anti-komunis yang mengangkat Suharto ke singgasana kekuasaan pada 1965.
Preman dikooptasi oleh tangan-tangan negara, terutama militer, menjadi sebuah struktur premanisme lebih luas serupa dengan cabang-cabang waralaba informal, yang diperbolehkan menjalankan sistem jatah preman mereka sendiri di tingkat lokal, dengan syarat hasilnya masuk ke struktur pemerintahan formal.
Agar lapisan-lapisan sistem ini bisa berfungsi, geng-geng preman juga diwajibkan menjalankan “tugas-tugas pemeliharaan rezim”, termasuk meneror dan menggertak para pembangkang dan pelbagai kekuatan sosial lainnya yang berpotensi mengguncang hubungan-hubungan kuasa yang setimbang, sambil mengumbar omong kosong perihal menjalankan ideologi negara.
Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru dalam praktiknya dicirikan oleh sejenis kegentingan khusus –langkah penyeimbangan yang sulit, di mana sejumlah besar badan negara dan aktor non-negara pengguna kekerasan tertungkus-lumus dalam persaingan, perundingan, persekutuan aji mumpung, dan siasat untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan serta perolehan keuangan: sebuah masyarakat jatah preman.
Setelah Reformasi 1998
Lalu, muncul kelompok-kelompok yang merupakan penubuhan dari kontradiksi dan ketegangan yang mencirikan politik jalanan Jakarta pasca-Orde Baru. Terlepas dari orientasi ideologis atau politiknya, kelompok-kelompok ini menyediakan jejaring solidaritas, identitas, dan struktur kesempatan untuk memenuhi kebutuhan material dalam konteks lingkungan sosial-ekonomi yang tak memberi banyak pilihan.
Meski berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti itu dapat menyediakan struktur kesempatan dan perlindungan bagi anggota dan lingkungannya, tetapi mereka melakukannya dalam cara yang justru memperkuat -alih-alih menentang- keadaan yang ada. Dengan itu mereka mereproduksi marjinalisasi ekonomi basis sosialnya. Berbagai ormas ini bekerja sebagai penjaga gerbang bagi jejaring klientelis yang tertutup.
Nilai guna kelompok-kelompok semacam itu jauh lebih mendasar tinimbang tukang pukul sewaan atau gengsterisme politik –peran-peran yang era kiwari terus menurun. Mereka umumnya langgas dari kendali langsung militer atau polisi, asalkan mereka mereproduksi peran “serupa-negara” dalam memelihara tatanan sosial-politik yang umumnya kondusif bagi kepentingan elite politik dan bisnis.
Dengan demikian, mereka menjadi kolaborator berharga, bahkan “aset bangsa”, yang bisa diberi konsesi-konsesi ekonomi dan politik.
Lalu, kemana aparat penegak hukum?