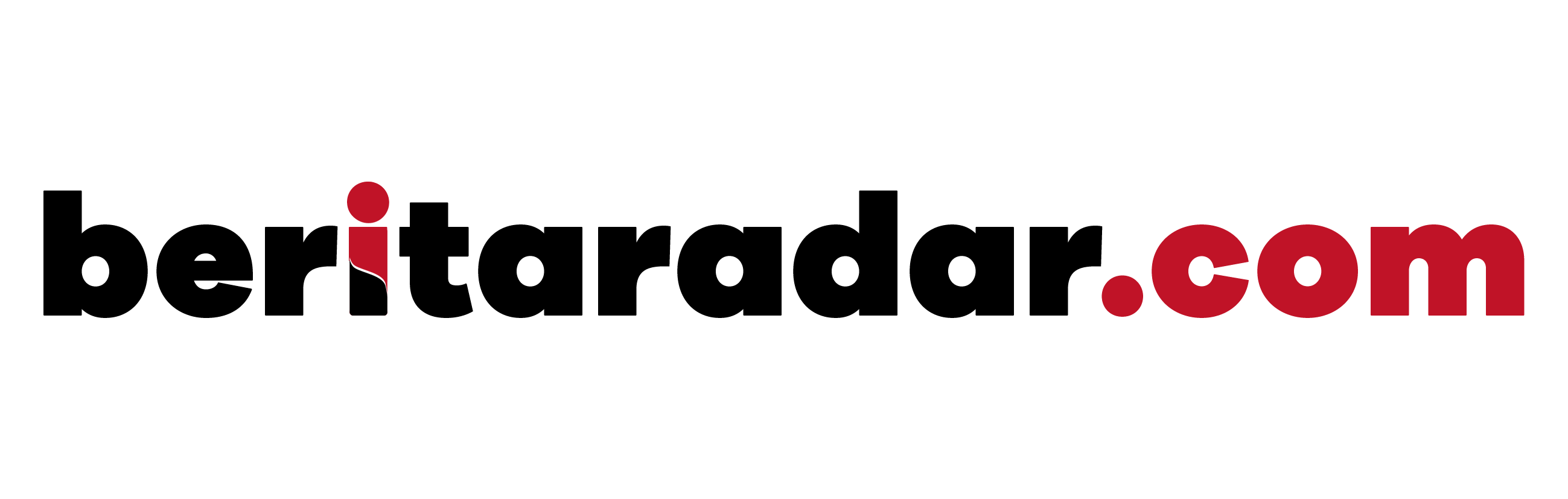WASHINGTON-Terdapat sebuah kenangan akan keindahan di samping kengerian yang menandai serangan tragis 11 September 2001. Badai telah melanda Timur Laut Amerika Serikat sehari sebelumnya, sehingga selanjutnya menimbulkan fenomena meteorologi langka di pagi itu yang dikenal sebagai “cuaca yang sangat cerah (severe clear).”
Di bukunya yang bertajuk “The Only Plane in the Sky: The Oral History of 9/11” dan baru akan terbit tanggal 10 September 2019 nanti, Garrett Graff menulis tentang “langit cerah tanpa awan yang menimbulkan kesan abadi pada semua orang yang menyaksikan apa yang terjadi di jam-jam berikutnya.” Graff mengutip orang-orang yang menggambarkan langit di atas New York dan Washington. “Biru yang cantik,” kata seorang petugas polisi Virginia. “Biru tua,” kata seorang staf Capitol Hill. “Sangat, sangat biru,” kata seorang koki di Manhattan. Beberapa orang lain mengingat langit cerah di atas kepala mereka sebagai “biru kobalt,” “biru cerulean,” dan “yang terbiru dari warna biru,” dan “yang Anda harap bisa dimasukkan ke dalam botol.”
Lebih dari 64 bab bukunya yang terbagi dengan baik, Graff, mantan editor di Politico, memberi kita “kisah-kisah mereka yang hidup dan mengalami 9/11, di mana mereka sedang berada saat itu, apa yang mereka ingat, dan bagaimana kehidupan mereka berubah.” Diambil dari ratusan wawancaranya sendiri dan dari pelaporan para jurnalis dan sejarawan lainnya, hasilnya luar biasa. Kurasi Graff atas kisah-kisah tersebut adalah hadiah yang tak ternilai untuk rakyat. Lagi pula, seperti yang diperhatikan Graff, musim gugur 2019 “akan menandai masuknya generasi pertama yang lahir setelah serangan 9/11 ke perguruan tinggi.”
Mereka adalah generasi baru yang “hampir tidak ingat hari itu sendiri.” Misi Graff adalah menawarkan kepada anak-anak muda Amerika yang belum pernah terluka itu sebuah buku yang akan mengajarkan mereka tentang apa yang terjadi pada serangan 9/11. Buku tersebut bebas dari pengaruh penyuntingan, ideologi, dan jeritan penuh duka. Alih-alih, buku Graff memberikan kita gambaran dan kesan yang menyedihkan, serta akibat yang ditimbulkannya.
Halaman demi halaman, para pembaca akan menemukan kata-kata yang mengejutkan atau membuat mereka marah, patah hati, atau mual. Mohamed Atta terlambat di Portland International Jetport di Maine untuk penerbangannya ke Boston, di mana ia akan menaiki American Airlines Penerbangan 11, pesawat yang ditabrakkannya ke Menara Utara World Trade Center di New York. Mike Tuohey, agen tiket di Portland, mengingat bahwa ia saat itu mengatakan dengan sopan santun profesional yang biasa: “Atta, jika Anda tidak pergi sekarang, Anda akan ketinggalan pesawat.” Semua orang yang membaca kisah ini akan bertanya apa jadinya jika Atta ketinggalan pesawat.
Beberapa halaman kemudian, kita akan menemukan rekaman kata-kata Amy Sweeney, pramugari di pesawat American Airlines Penerbangan 11, berbicara di Airfone kepada seorang manajer di lapangan. “Ada sesuatu yang salah. Saya khawatir pilot tidak memegang kendali. Saya bisa melihat air. Saya bisa melihat bangunan. Kami terbang rendah. Kami terbang sangat rendah. Ya Tuhan. Kami terbang terlalu rendah.” Dalam beberapa detik, pesawat itu pun menabrak menara WTC.
Ada banyak hal dalam buku ini tentang keberanian petugas pemadam kebakaran dan petugas keamanan selama menanggapi serangan. Pastor Mychal Hakim adalah seorang pendeta di Departemen Pemadam Kebakaran New York, satu-satunya pendeta yang memasuki menara hari itu, yang menyelenggarakan ritus terakhir (last rite). Dia meninggal di Menara Utara. “Para pemadam kebakaran mengevakuasi tubuhnya,” kata seorang biarawan. “Karena mereka sangat menghormati dan mencintainya, mereka tidak ingin meninggalkannya di jalan. Mereka segera membawanya ke Gereja Santo Petrus di dekatnya.”
Rick Rescorla adalah mantan penerjun payung Inggris yang menjabat wakil presiden keamanan untuk Morgan Stanley di Menara Selatan. Mengabaikan jaminan Otoritas Bandara bahwa menara itu aman, dia berkata: “Saya akan membawa orang-orang saya untuk keluar dari sini.” Rescorla berhasil menyelamatkan ratusan nyawa dalam proses itu tetapi kehilangan nyawanya sendiri.
Namun kebaikan orang-orang biasalah yang meninggalkan kesan paling dalam. Kita membaca, misalnya, tentang reaksi Heather Ordover, seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah yang terletak tiga blok di selatan World Trade Center, tepat setelah pesawat pertama menabrak menara. “Kita semua mendengar raungan mesin,” kata Ordover, “seperti ledakan bom dalam film perang. Lalu ada kilatan cahaya.” Ketika anak-anak di kelasnya berlari ke jendela, di mana mereka melihat asap dan puing yang berjatuhan, naluri protektifnya sebagai guru pun muncul. “Saya berlari kembali ke depan ruangan, berteriak kepada anak-anak untuk duduk dan menulis tentang apa yang baru saja mereka lihat, upaya apa pun untuk menjauhkan mereka dari jendela.”
Ada banyak kisah lainnya tentang sifat tanpa pamrih dan kebaikan manusia. Banyak operator panggilan darurat 911 yang memberitahu orang-orang yang terperangkap di lantai paling atas, yang menelepon untuk mengatakan, “Saya akan mati, bukan?”, bahwa bantuan akan segera datang dan mereka tidak akan mati. Meski itu tidak benar, pernyataan itu jelas berasal dari kebaikan hati. Dalam buku Graff, detail kecil semacam itu diizinkan berbicara sendiri dan menunjukkan kefasihan bercerita yang menonjol.
Sementara itu, “Fall and Rise: The Story of 9/11” karya Mitchell Zuckoff, adalah pelengkap monumental untuk buku Graff. Mantan wartawan di Boston Globe, Zuckoff sekarang menjadi profesor di Boston University. Zuckoff telah berusaha untuk menghidupkan kembali prosa dramatis yang disusun oleh Graff lewat puzzle lisan. Zuckoff menekankan bahwa narasinya “tidak memiliki lisensi atas fakta, kutipan, karakter, atau kronologi.” Tujuan bukunya, seperti buku Graff, ialah untuk melestarikan memori ketika Amerika diserang, “untuk menunda serangan 9/11 terlupakan dalam sejarah.”
Deskripsi Zuckoff tentang pembajakan pesawat, meliputi kekacauan di atas pesawat, tabrakan pesawat, penghancuran menara, upaya penyelamatan, kematian, dan berbagai kesengsaraan selanjutnya sangatlah luar biasa dalam hal ketegangannya. Yang terutama menggerakkan perasaan pembaca adalah kisah tentang bagaimana Brian Clark dan Stan Praimnath saling bertemu di reruntuhan. Keduanya tak saling mengenal dan masing-masing bekerja di lantai 84 dan 81 Menara Selatan WTC.
Ketika Brian pertama kali mengulurkan tangan untuk membantu Stan yang kebingungan, Brian terkejut karena ditanya Stan apakah dia percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai tanggapan, Zuckoff menulis, “Brian terbata-bata mengisahkan ibadah gereja setiap hari Minggu. Dia bertanya-tanya apakah pria yang dia coba selamatkan telah kehilangan akal sehatnya.” Di tengah musibah, di lantai 81, mereka berjabat tangan, saling berkenalan, dan bersumpah untuk menjadi saudara seumur hidup. Brian kemudian melingkarkan lengannya di bahu Stan dan berkata, “Ayo pulang.”
Brian dan Stan berhasil keluar dari reruntuhan dalam keadaan selamat. Di tempat lain, kolega Brian tetap terjebak dalam puing-puing yang hancur. Di antara mereka, tulis Zuckoff, terdapat seorang pialang bernama Randy Scott, “ayah yang menyenangkan, pengendara sepeda motor, menikah dengan bahagia dan memiliki tiga anak perempuan.” Tanpa ada cara lain untuk mencari bantuan, Scott menulis permohonan: “lantai 84/kantor barat/12 orang terperangkap.” Dia melemparkan catatannya ke luar jendela, “mengepak-ngepak di antara potongan-potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya yang dihembuskan dari kedua menara.” Sebelum Scott melemparkan kertasnya, dia “menekankan jari berlumuran darah ke kertas itu,” meninggalkan DNA yang nantinya akan mengidentifikasi dia sebagai penulis catatan.
Bab dalam buku Zuckoff tentang pesawat United Penerbangan 93, yang jatuh ke tanah dekat Shanksville, Pennsylvania, ditulis secara mencekam. Kisah ini, secara berurutan, adalah penerbangan keempat dari empat pesawat yang dibajak. Para penumpang serta awak kapal mengetahui niat para pembajak, setelah berkomunikasi dengan para keluarga dan pejabat melalui Airfones di dalam pesawat. “Pengetahuan itu,” tulis Zuckoff, “menjadi motivator yang kuat. Itu mengubah mereka dari korban sandera menjadi pejuang perlawanan.” Zuckoff menggambarkan percakapan para penumpang dengan pasangan dan orang tua mereka di daratan sebagai “permadani lisan yang berhiaskan keikhlasan, peringatan, keberanian, keteguhan hati, dan cinta.”
Ada saat-saat di mana upaya Zuckoff untuk menghidupkan setiap karakternya dapat terbaca dengan sangat sentimental. John Ogonowski, pilot American Airlines 11, digambarkan sebagai “anak desa yang tampan,” senyumnya menorehkan “kerutan dalam di kulit kemerahan di sekitar mata birunya.” Sementara itu, CeeCee Lyles, pramugari heroik di pesawat United Penerbangan 93, “memiliki mata cokelat yang berkedip dan kecintaan akan pakaian bagus yang membungkus apik sosok atletisnya.”
Tetapi kisah-kisah semacam itu tidak merusak kebenaran naratif dari buku Zuckoff. Menghidupkan kembali momen ketika pesawat kedua menabrak Menara Selatan, ia menulis bahwa “sentakan di bagian tengah menyebabkan lantai atas berputar seperti anggota tubuh petinju yang dihantam oleh pukulan yang tak terduga.” Kisah tersebut mencengangkan dan hampir ajaib dalam membangkitkan sebuah serangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Bersamaan dengan suara-suara dari sejarah lisan Graff, misalnya panggilan darurat dari lantai-lantai teratas dan upaya penyelamatan yang tidak akan pernah datang, kata-kata seperti ini akan membuat ingatan akan serangan 9/11 tetap abadi dalam kenangan. (*)