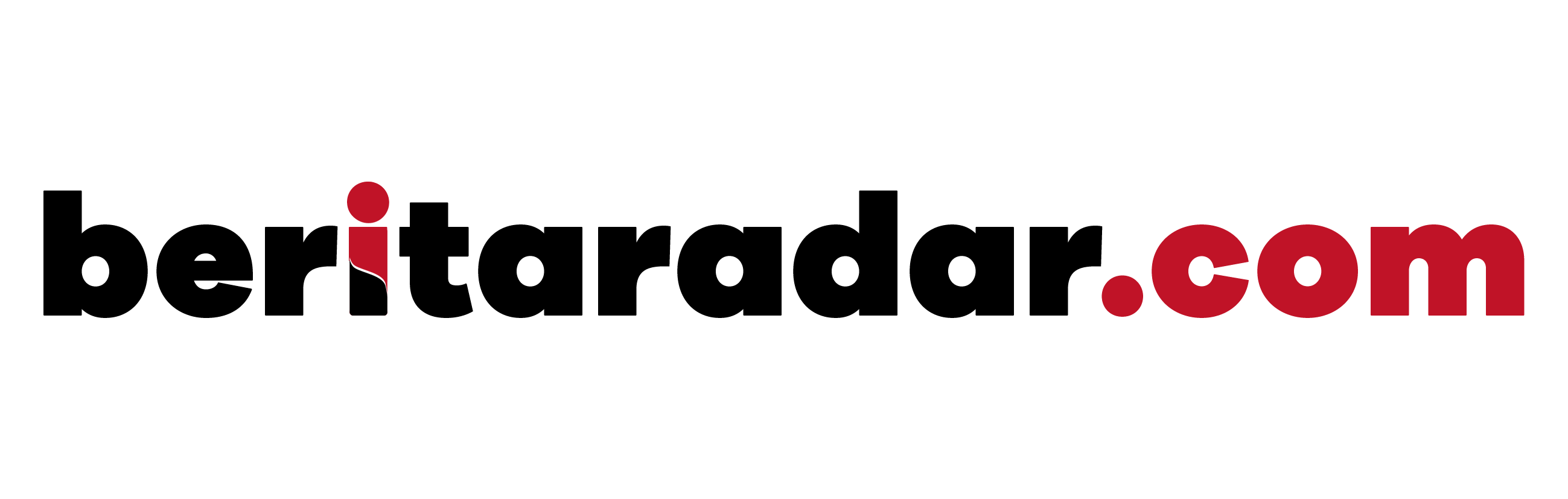Cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat derajat para petani lewat redistribusi lahan 9 juta hektare (ha) masih jauh panggang dari api.
Buktinya, sampai hari ini, bertepatan dengan peringatan ke-59, Jokowi yang memulai kepemimpinan pada 2014, cuma janji memberikan berbagai kebijakan yang bisa menguatkan pembangunan di sektor pertanian dan kesejahteraan kaum petani.
Yang teranyar, program reforma agraria diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. Dasar hukum ini mengatur subjek penerima lahan agraria dengan tujuan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Namun, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi masyarakat nirlaba, Jokowi tak juga berhasil menjalankan janji Reforma Agraria. Tidak sedikit pun.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan hal ini tercermin dari janji redistribusi lahan seluas 9 juta ha yang tak kunjung diterima oleh petani. Padahal, luasan lahan itu menjadi pokok utama program Reforma Agraria ala Jokowi.
“Pemerintah tetap mempertontonkan kekeliruan reforma agraria dengan membiarkan krisis agraria dialami kaum tani Indonesia dan tidak diatasi dengan serius,” ucap Dewi, Senin (23/9).
Begitu juga dengan penyelesaian konflik agraria dan perbaikan ekonomi, serta produksi pertanian yang tak kunjung diterima petani. Bahkan, di sejumlah tempat, banyak lahan petani, wilayah adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, hingga masyarakat miskin kaum pertanian yang diambil alih secara paksa dan sepihak.
Pengambilalihan, sambung dia, dilakukan oleh kalangan pemerintah dan perusahaan yang melegitimasi oleh keputusan pemerintah. Berdasarkan data KPA pada akhir 2017, sekitar 71 persen luasan lahan di Indonesia di antaranya dikuasai korporasi kehutanan.
Kemudian, 16 persen selanjutnya dimiliki oleh korporasi perkebunan skala besar dan tujuh persen dalam genggaman para konglomerat. Sisanya, kurang dari enam persen dipegang oleh petani kecil yang tersebar di seluruh Tanah Air.
“Pengambilalihan tetap menggunakan cara-cara lama, yaitu melibatkan tentara, dan polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan proyek strategis nasional,” imbuh Dewi.
Lebih lanjut, pengambilalihan lahan pertanian memunculkan konflik agraria yang kerap merugikan masyarakat tani. Data KPA mencatat luas lahan konflik agraria tembus 2,86 juta ha pada 2014.
Jumlahnya sempat menurun pada 2015 menjadi 400,43 ribu ha, namun kemudian meningkat drastis menjadi 1,26 juta ha pada 2016. Sementara luasan lahan konflik agraria mencapai 520,49 ribu ha pada 2017 dan 807,17 ribu ha pada 2018.
“Konflik agraria masih ada, dan cenderung bertambah dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini karena terjadi ganti rugi yang tak sebanding,” terang dia.
Memang, Pemerintahan Jokowi juga sudah merealisasikan program bagi-bagi sertifikasi lahan untuk mendukung pemilikan tanah bagi para petani kecil. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, pemerintah memberikan 967.490 sertifikat pada 2015 dan 1.168.095 sertifikat pada 2016.
Kemudian, meningkat menjadi 5,4 juta pada 2017 dan 9,4 juta pada 2018. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa menebar 9 juta sertifikat lahan kepada masyarakat.
Lalu, pemerintah juga menggagas program perhutani sosial dengan target masa konsesi mencapai 12,7 juta ha. Namun, realisasinya baru mencapai 2,6 juta ha yang dibagikan. Sayangnya, realisasi ini lagi-lagi hanya menjadi pemanis lantaran akar masalah reforma agraria tetap belum mampu diselesaikan oleh Jokowi.
Tak ketinggalan, ia melihat tidak ada peran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membantu kalangan petani. Hal ini tercermin dari sikap para lembaga legislatif yang seakan tidak peduli dengan kaum petani dengan mempermulus jalan sejumlah aturan yang secara jelas bakal merugikan petani.
Salah satunya, terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Menurutnya, RUU itu justru membuat negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga negara Indonesia
“Berbulan-bulan kami bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah menyampaikan masukan dan usulan pembatalan rencana pengesahan RUU Pertanahan. Tapi kami tidak didengar,” kata Dewi.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memandang program Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah dalam lima tahun terakhir memang punya nilai plus dan minus. Dari sisi positif, program bagi-bagi sertifikat setidaknya memberikan kepastian kepada petani.
Meskipun, memang belum sepenuhnya diimbangi dengan penanganan yang baik terhadap konflik agraria yang ada. Apalagi, sertifikasi itu sendiri bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik.
Namun, negatifnya, kebijakan pemerintah saat ini yang masih lebih mengutamakan lahan untuk pembangunan infrastruktur turut membuat harga makin melambung dari waktu ke waktu. Secara tidak langsung, ini membuat para pemilik modal dapat menguasai lahan, sementara rakyat kecil kesulitan.
Belum lagi, soal tingkat kesejahteraan petani yang tak kunjung membaik dalam lima tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal yang diterima petani pada 2014 berkisar Rp43 ribu sampai Rp45 ribu per bulan. Sementara, upah riil sekitar Rp37 ribu sampai Rp39 ribu per bulan.
Kondisi ini tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun ini. Pada Januari-Juni 2019, upah nominal petani memang meningkat mencapai kisaran Rp53 ribu sampai Rp54 ribu per bulan. Namun, upah riil yang menunjukkan kemampuan beli petani tetap berada di kisaran Rp38 ribu per bulan.
“Ini pertanda, berbagai program penguatan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani belum benar-benar ampuh meningkatkan daya beli petani itu sendiri,” ucapnya. (*)